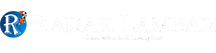Terjebak Impor Kapas Triliunan, Padahal Bisa Produksi Sendiri

Ilustrasi Kapas. -Foto Pixabay---
Radarlambar.bacakoran.co – Meski dikenal sebagai negara agraris dengan bentang alam tropis yang subur, Indonesia masih harus mengandalkan impor kapas dalam jumlah besar. Ironisnya, komoditas yang sebenarnya bisa ditanam sendiri ini justru dibeli dari luar negeri dengan nilai fantastis, bahkan menyentuh belasan triliun rupiah per tahun.
Data menunjukkan, sepanjang tahun 2024, Indonesia mengimpor sekitar 405 ribu ton kapas dengan nilai mencapai Rp13,38 triliun. Angka ini memang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap memperlihatkan betapa dalamnya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan luar. Dalam empat tahun terakhir, nilai impor kapas tak pernah turun dari angka Rp13 triliun, bahkan sempat melonjak hingga hampir Rp22 triliun pada 2022 saat harga global meningkat tajam.
Mayoritas kapas tersebut datang dari negara-negara seperti Brasil, Argentina, Australia, China, hingga Yunani dan Spanyol. Ketergantungan ini terjadi akibat minimnya pasokan domestik, sementara industri tekstil dalam negeri terus tumbuh dan membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa produksi kapas lokal masih sangat rendah di tahun 2020 produksi nasional hanya mencapai 127 ton dari 703 hektare lahan artinya produktivitasnya pun menyedihkan sekitar 180 kg per hektare—jauh di bawah standar ideal yang bisa mencapai 1,5 hingga 2,8 ton per hektare seperti di NTB dan Sulawesi Selatan.
Padahal, Indonesia pernah punya sejarah kuat dalam budidaya kapas. Di era kolonial, tanaman ini menjadi salah satu komoditas utama yang menunjang industri tenun rakyat. Wilayah-wilayah seperti NTT, Sulsel, Jateng, Bali, hingga NTB secara agroklimat sangat cocok untuk pengembangan kapas.
Sayangnya, beberapa faktor terus menahan potensi ini. Alih fungsi lahan, cuaca yang tak menentu, minimnya harga jual, serta rendahnya daya tarik ekonomi membuat petani lebih memilih komoditas lain seperti jagung dan kedelai. Padahal, Indonesia sudah memiliki varietas unggul seperti Kanesia 8 dan Kanesia 9 yang berumur pendek, tahan terhadap iklim tropis, dan mampu memenuhi standar kualitas industri tekstil.
Sayangnya, adopsi varietas tersebut di lapangan masih rendah. Minimnya informasi, pendampingan teknologi, serta lemahnya dukungan kelembagaan membuat para petani enggan beralih ke kapas. Banyak dari mereka bahkan menganggap komoditas ini tidak menjanjikan secara ekonomi. Ketidakhadiran kemitraan yang kuat antara petani dan industri tekstil juga memperparah situasi, karena rantai pasok menjadi tidak efisien.
Pemerintah sebenarnya sempat mencoba menghidupkan kembali produksi kapas dengan memberi subsidi benih dan pupuk serta program padat karya selama pandemi. Namun, tanpa konsistensi dan penguatan pembinaan, upaya ini hanya bersifat sementara dan tidak berdampak jangka panjang.
Untuk keluar dari jeratan impor, Indonesia membutuhkan langkah konkret. Salah satunya adalah pemetaan dan optimalisasi lahan-lahan marginal di wilayah potensial seperti NTB, Sulsel, dan Jateng. Substitusi impor pun harus dikejar melalui adopsi varietas unggul lokal maupun transgenik yang sesuai dengan kondisi agroekosistem tropis.
Selain itu, pengembangan teknologi tepat guna, irigasi efisien, digitalisasi rantai pasok, serta penguatan kemitraan antara petani dan industri tekstil menjadi kunci utama. Mengingat ketatnya persaingan dengan komoditas lain, pemerintah juga perlu menyusun skema insentif yang menjanjikan bagi petani kapas.
Saat ini, lebih dari Rp13 triliun per tahun dikeluarkan untuk membeli kapas dari luar negeri. Padahal, negeri ini memiliki varietas lokal unggulan, sumber daya genetik melimpah, dan lahan luas yang bisa dimanfaatkan. Dengan komitmen yang jelas dan sinergi lintas sektor, Indonesia bukan hanya bisa mandiri kapas, tetapi berpotensi besar menjadi pemain utama dalam ekspor kapas tropis dunia. (*/rinto)