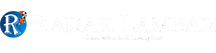Sarjana Menganggur: Ketika Gelar Tak Lagi Menjadi Jaminan

Foto: CNBC INDONESIA--
Radarlambar.bacakoran.co- Dulu, gelar sarjana dianggap sebagai tiket menuju masa depan yang mapan. Namun kenyataan berkata lain. Kini, jumlah lulusan universitas di Indonesia yang belum bekerja terus bertambah. Alih-alih membuka pintu peluang, ijazah yang dibanggakan justru menjadi beban di tengah pasar kerja yang semakin ketat dan jenuh.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Pada 2014, pengangguran bergelar sarjana tercatat sebanyak 495.143 orang. Enam tahun kemudian, jumlah itu melonjak nyaris dua kali lipat menjadi 981.203 orang. Meski pada 2024 turun menjadi 842.378 orang, angka itu tetap menyiratkan masalah struktural yang belum terselesaikan.
Pandemi Covid-19 memperparah keadaan. Dunia kerja lumpuh, rekrutmen terhenti, dan ribuan lulusan baru harus memulai karier di tengah krisis global. Namun persoalan ini lebih dalam dari sekadar pandemi. Ia mencerminkan ketimpangan antara sistem pendidikan dan realitas dunia kerja.
Lulusan SMA masih mendominasi jumlah pengangguran secara keseluruhan—mencapai 2,51 juta pada 2023. Namun kelompok ini cenderung lebih adaptif, mampu langsung masuk ke sektor informal atau pekerjaan teknis yang tidak menuntut latar belakang akademik tinggi.
Sebaliknya, lulusan sarjana sering terjebak dalam jurang antara idealisme dan kenyataan. Banyak yang menolak pekerjaan di luar bidang studi, atau menunggu posisi bergengsi yang tidak kunjung tersedia. Fenomena ini dikenal sebagai aspirational mismatch—ketika harapan melampaui kapasitas pasar. Di sisi lain, ada pula reservation wage gap—harapan gaji tinggi yang tidak sebanding dengan daya serap industri.
Dalam konteks ini, lulusan diploma justru menunjukkan tren yang lebih stabil. Pada 2014, jumlah penganggur dari jalur vokasi tercatat 193.517 orang. Angka ini naik menjadi 305.261 pada 2020, namun turun signifikan menjadi 170.527 pada 2024. Stabilitas ini tak lepas dari pendekatan pendidikan vokasi yang lebih terfokus pada kebutuhan pasar, dengan penekanan pada keterampilan praktis dan kesiapan kerja.
Kendala utama bukan terletak pada jumlah lapangan kerja, melainkan ketidaksesuaian keterampilan. Kurikulum banyak perguruan tinggi belum mampu mengikuti irama perubahan zaman. Keterhubungan antara kampus dan dunia industri masih longgar. Sementara itu, semangat kewirausahaan belum menjadi arus utama di lingkungan akademik.
Untuk mengatasi ini, perubahan perlu dilakukan sejak dari hulu. Kampus harus mulai merancang ulang pendekatan pendidikannya, dengan menanamkan keterampilan yang lebih aplikatif dan adaptif—baik dalam bidang digital, komunikasi, maupun kolaborasi lintas disiplin. Magang dan kemitraan dengan industri perlu diperluas. Tak kalah penting, mahasiswa perlu dibekali mental sebagai pencipta lapangan kerja, bukan sekadar pencari pekerjaan.
Kenyataan bahwa gelar sarjana tak lagi menjamin pekerjaan bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari tantangan untuk berbenah. Jika pendidikan tinggi mampu beradaptasi, dan lulusan mampu menjembatani antara mimpi dan realita, maka masa depan tenaga kerja Indonesia masih bisa diarahkan ke jalan yang lebih cerah.
Indonesia tidak kekurangan talenta. Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu mengenali, memfasilitasi, dan memberdayakan potensi itu agar tidak berakhir dalam antrean panjang pengangguran terdidik.(*)