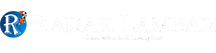Polemik Ijazah Palsu dan Fakta Soal Uji Karbon: Bisa Deteksi Keaslian Dokumen?

Polemik Ijazah Palsu dan Fakta Soal Uji Karbon Bisa Deteksi Keaslian Dokumen. Foto/net--
Radarlambar.bacakoran.co - Polemik terkait keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat di tengah publik. Meski telah berulang kali dibantah, isu ini masih terus berputar, kali ini dengan desakan agar dilakukan uji karbon terhadap dokumen ijazah tersebut.
Di sisi lain, masyarakat pun mulai bertanya-tanya, apakah uji karbon benar-benar bisa menjadi alat untuk membuktikan keaslian sebuah dokumen? Bagaimana sebenarnya metode ini bekerja dan sejauh apa efektivitasnya dalam konteks dokumen modern?
Ciri Fisik Ijazah Asli
Untuk memastikan keaslian ijazah secara umum, terdapat beberapa aspek fisik yang bisa diperiksa. Pertama, penggunaan jenis kertas khusus yang diproduksi oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Kertas ini memiliki tekstur dan ketebalan yang berbeda dari kertas biasa dan sulit dipalsukan.
Kedua, keberadaan hologram permanen yang telah menyatu dengan lembar ijazah. Hologram ini umumnya menampilkan logo resmi institusi pendidikan dan tidak bisa dilepas atau digandakan begitu saja.
Ketiga, nomor seri unik yang hanya bisa dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut. Nomor ini bisa diverifikasi langsung ke pihak universitas atau sekolah terkait.
Verifikasi ini sejatinya sudah cukup untuk membedakan ijazah asli dan palsu tanpa perlu menempuh metode ilmiah kompleks seperti uji karbon.
Uji Karbon, Bukan untuk Dokumen Modern?
Uji karbon—atau penanggalan radiokarbon—merupakan teknik ilmiah untuk memperkirakan usia benda organik yang berumur hingga puluhan ribu tahun. Metode ini mengukur sisa isotop karbon-14 (C-14) dalam material seperti kayu, tulang, kain, atau arang, yang dulunya menyerap karbon dari atmosfer.
Dikembangkan pertama kali pada 1940-an, metode ini telah digunakan dalam berbagai penelitian arkeologi dan sejarah. Namun, penanggalan karbon tidak dirancang untuk mendeteksi keaslian dokumen modern seperti ijazah yang baru berusia beberapa dekade.
Uji karbon hanya bisa memberikan perkiraan usia kertas, bukan isi dokumen atau otentisitas legalnya. Selain itu, kertas bisa saja diproduksi lebih awal dari waktu pencetakan dokumen, dan tinta yang digunakan belum tentu bisa diuji dengan metode yang sama.
Prosedur Rumit, Hasil Terbatas
Dalam praktiknya, uji karbon melibatkan serangkaian tahapan pembersihan fisik dan kimiawi untuk menghilangkan kontaminasi. Metode paling canggih, yaitu Accelerator Mass Spectrometry (AMS), mampu mengukur jumlah atom karbon-14 langsung dari sampel dengan sangat presisi. Namun, proses ini bersifat destruktif—artinya sampel akan hancur dalam prosesnya.
Sampel yang diperlukan pun harus cukup besar dan dalam kondisi bersih. Kontaminasi sekecil apa pun bisa membuat hasilnya tidak akurat. Dan yang tak kalah penting, uji ini hanya mampu menentukan umur bahan organik, bukan membuktikan siapa yang mencetak dokumen atau apakah ijazah itu sah secara hukum.
Kesimpulan: Cek Legalitas, Bukan Jejak Karbon
Dalam kasus polemik ijazah, metode verifikasi seharusnya tetap mengacu pada mekanisme legal dan administratif—seperti pengecekan arsip di institusi pendidikan, verifikasi nomor seri, atau analisis digital terhadap sistem pendaftaran.
Uji karbon mungkin terdengar ilmiah dan spektakuler, namun penerapannya untuk mendeteksi keaslian ijazah tidaklah relevan secara praktis maupun ilmiah. Justru, fokus pada pembuktian legal dan dokumentasi institusional adalah cara paling rasional dalam menyikapi isu ini.
Dengan informasi yang tepat, publik diharapkan tidak mudah terseret arus disinformasi yang sering kali memanfaatkan istilah ilmiah tanpa konteks yang benar. (*)